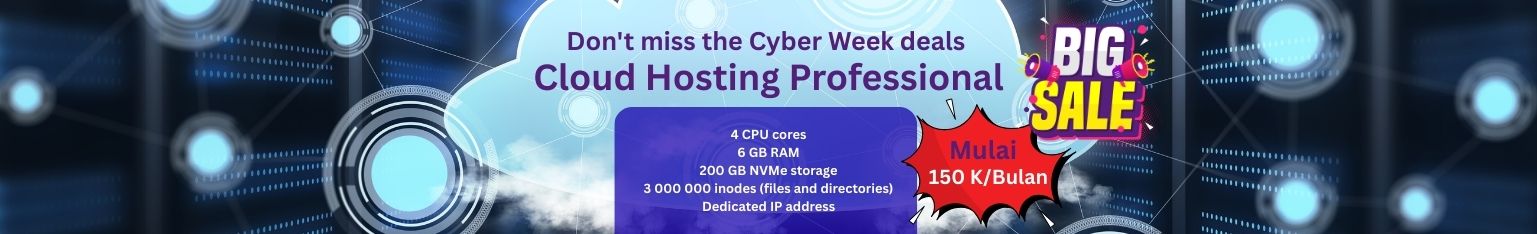SURAU.CO – Kiai Modjo memiliki nama asli Muslim Mochammad Khalifah. Ia lahir di Surakarta pada tahun 1792. Publik mengenal sosoknya sebagai ulama karismatik sekaligus panglima perang. Ia menjadi orang kepercayaan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa berlangsung. Perannya tidak hanya sebatas strategi militer. Kiai Modjo adalah ideolog yang mengubah perlawanan menjadi perang suci.
Latar Belakang Keluarga dan Hubungan dengan Diponegoro
Kiai Modjo berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Iman Abdul ‘Arif, adalah ulama besar bergelar Kiai Baderan. Ibunya, R.A. Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwana III. Meskipun berdarah biru, ia tumbuh di luar lingkungan keraton. Ayahnya memilih jalan dakwah sebagai pengabdian hidupnya. Pilihan ini membentuk karakternya sejak dini.
Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro secara silsilah adalah saudara sepupu. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwana III dari istri selir. Keduanya sama-sama hidup jauh dari kemewahan istana. Hubungan mereka semakin erat setelah Kiai Modjo menikahi Raden Ayu Sepuh. Ia adalah janda dari paman Diponegoro. Karena pernikahan ini, Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Modjo dengan sapaan hormat “paman”.
Peran sebagai Ulama dan Ideolog Perang Jawa
Pengetahuan agama Kiai Modjo tertempa kuat oleh ayahnya. Ia juga sempat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah. Sekembalinya ke tanah air, ia meneruskan peran ayahnya mengelola pesantren. Dari sanalah ia menghimpun banyak pengikut setia. Bersama para santrinya, ia mengobarkan gerakan menentang pemurtadan di kalangan bangsawan. Cita-citanya adalah mendirikan pemerintahan berbasis syariat Islam di tanah Jawa.
Pangeran Diponegoro melihat kesamaan visi ini. Saat Perang Jawa meletus, Diponegoro mencari ulama yang mampu memberi landasan Al-Quran untuk perang sabil. Ia berdiskusi dengan pamannya, Pangeran Mangkubumi, di Gua Selarong. Diponegoro menolak usulan memilih ulama dari Yogyakarta. Ia menilai masih kurang memiliki kapasitas. Sebaliknya, ia memanggil dua ulama yang terkenal sangat takwa. Mereka adalah Kiai Kuweron yang sudah sepuh dan Kiai Modjo yang saat itu berusia 33 tahun.
Kiai Modjo bergabung sejak awal perang gerilya. Ia berhasil mengubah citra perlawanan dari “pemberontakan” menjadi “perang sabil”. Label ini membakar semangat juang melawan Belanda, yang kafir. Kemampuannya merekrut tokoh sangat luar biasa. Ia berhasil mengajak 88 kiai desa, 11 syekh, dan puluhan pemuka agama lainnya untuk bergabung dalam barisan Diponegoro.
Penangkapan dan Pengasingan
Kekuatan Kiai Modjo membuat Belanda gerah. Pihak kolonial menganggapnya sebagai otak dan dalang fanatisme pasukan Diponegoro. Pada November 1828, Kiai Modjo mencoba berunding secara sepihak dengan Belanda di Melangi. Namun, perundingan itu ternyata hanyalah jebakan. Pasukan Belanda di bawah komando Letnan-Kolonel Joseph Le Bron de Vexela telah mengepungnya.
Pada 12 November 1828, pasukan Belanda berhasil mencegat pasukan Kiai Modjo di Babadan. Ia diberi pilihan menyerah tanpa syarat atau bertempur dalam kondisi terkepung dan ia memilih menyerah bersama 400 pengikutnya. Ia kemudian dibawa ke Salatiga. Dengan jiwa besar, ia meminta Belanda membebaskan sebagian besar pengikutnya. Belanda mengabulkan permintaan itu. Namun, mereka menahan Kiai Modjo dan orang-orang terdekatnya. Belanda memperlakukannya lebih tegas daripada bangsawan keraton yang membelot. Sebab, pengaruh ideologinya dianggap sangat berbahaya.
Pada 17 November 1828, Belanda mengirim Kiai Mojo ke Batavia. Mereka memutuskan untuk mengasingkannya ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Pengasingan ini menjadi pukulan telak bagi Pangeran Diponegoro. Perang Jawa akhirnya berakhir dua tahun setelah Belanda menangkap Kiai Mojo.
Warisan di Tanah Buangan: Lahirnya Kampung Jawa Tondano
Di Tondano, Kiai Modjo tidak berhenti berjuang. Ia beralih dari medan perang ke medan dakwah. Menurut Habib H. Husen Assagaf, Imam Masjid Agung Al-Falah Kampung Jawa Tondano, Kiai Modjo adalah penyiar Islam pertama di seluruh Minahasa (Ma’u & Bukido, 2023). Ia tiba di Minahasa pada tahun 1830, setahun sebelum misionaris Kristen dari Jerman datang dengan dukungan penuh Belanda.
Belanda menempatkan Kiai Modjo dan para pengikutnya di sebuah area rawa-rawa. Dengan keahlian bercocok tanam, mereka mengubah lahan tak berpenghuni itu menjadi persawahan subur. Sikapnya yang jujur, adil, dan dermawan menarik simpati penduduk lokal. Para Walak (kepala suku) Minahasa terkesan bukan karena retorika, melainkan karena keteladanan perilakunya. (Ma’u & Bukido, 2023).
Interaksi ini melahirkan asimilasi budaya yang unik. Banyak pengikut Kiai Mojo menikah dengan gadis-gadis asli Minahasa. Perkawinan ini menjadi cikal bakal komunitas Kampung Jawa Tondano (Jaton). Beberapa tradisi Jawa berpadu dengan budaya Minahasa, seperti:
Perkawinan: Prosesi ‘sungkeman’ dari adat Jawa dalam upacara pernikahan di Minahasa.
Kelahiran: Tradisi ‘tingkep’ (syukuran tujuh bulan kehamilan) dan ‘puputan’ (aqiqah setelah tali pusar lepas) tetap lestari.
Kematian: Peringatan hari ketiga, ketujuh, hingga keseratus setelah kematian masih menjadi tradisi .
Ziarah: Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan, mengenalnya sebagai ‘punggoan’, menjadi ritual penting untuk mendoakan leluhur.
Lebaran Ketupat: Menciptakan tradisi Lebaran Ketupat pada hari ketujuh Syawal. Tradisi ini menjadi sarana silaturahmi yang mempererat hubungan antarumat beragama di Minahasa
Kiai Modjo wafat pada 20 Desember 1849 dalam usia 57 tahun dan dimakamkan di Kampung Jawa Tondano, Minahasa. Warisannya hidup abadi. Masyarakat mengenangnya tidak hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai perintis dakwah dan pembaharu budaya yang menciptakan harmoni di tanah pengasingannya. (Tri/dari berbagai sumber)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.